Saya masih ingat betul hari itu. Sebelas anak duduk di depan saya, berjejer kurang rapi. Ada yang menatap lantai, lainnya gelisah duduk di kursi, menggosok-gosok pantatnya yang tidak gatal, seolah di sana ada kupon undian.
“Ada yang sudah bisa membaca?” Saya bertanya seraya menulis di papan tulis. Satu anak mengangkat tangan. A, B, C, D, Pak, akunya. Yang lain hening, mengiyakan lagu D’Masiv: “Diam Tanpa Kata”.
Saya yakin sekali, muridku bukan anak-anak malas sehingga tidak bisa. Di rumah, mereka mungkin belum pernah bersentuhan dengan huruf. Buta huruf, dalam arti yang paling literal. Dan sekolah seperti Pertamina, mesti memulai dari nol: harus mengajari mereka menggenggam pensil, menulis garis, sesekali menceboki juga. Percayalah, itu bukan pekerjaan mudah. Membikin cepat tua.
Tetiba sebuah tanya berkelebat di kepala, kenapa anak-anak kita terlambat bisa membaca?Kenapa mereka baru mengenal huruf ketika sudah duduk di bangku sekolah dasar?
Kalau dipikir-pikir, memang tidak ada tempat yang benar-benar “mengajarkan” anak-anak kita membaca. Di taman kanak-kanak, kurikulumnya lebih banyak bermain, bernyanyi, dan bersosialisasi. Tidak ada pelajaran membaca secara sistematis, karena prinsipnya memang “belajar sambil bermain.” Di SD kelas satu pun, tidak ada pelajaran khusus membaca, anak-anak langsung dihadapkan dengan teks, yang mengandaikan mereka sudah bisa membaca.
Sebagai guru PJOK, saya sebenarnya tidak terlalu masalah, karena fokus besar saya ada pada keterampilan fisik. Namun, saya kemudian menyadari bahwa literasi dasar yang kurang, ternyata berpengaruh pada kemampuan anak-anak memahami intruksi sederhana, disuruh ke kanan, lari ke kiri, disuruh ke kiri, lari ke kantin.
Lalu, siapa yang bertugas mengajari anak membaca? Secara diam-diam, sistem mengharapkan orangtua, tapi harapan itu bertepuk sebelah tangan. Sebab asumsi itu tidak pernah dikatakan dengan tegas. Pemerintah tidak pernah secara jelas memberi tahu bahwa tanggung jawab membaca harus dimulai dari rumah. Tidak ada program besar yang mengarahkan orangtua bagaimana mengajari anak mengenal huruf.
Akibatnya, anak-anak seolah dilempar ke sekolah tanpa bekal apa pun, di sekolah memang ada MBG, tapi itu bekal perut, bukan kepala. Akhirnya, guru mesti menjadi juru selamat yang mengenalkan alfabet, sesuatu yang mestinya sudah dikenal jauh sebelumnya.
Kondisi ini sebenarnya memperlihatkan sesuatu yang hilang dalam kebijakan pendidikan nasional. Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum PAUD dan transisi ke SD menekankan pentingnya “masa peralihan yang menyenangkan” dan “pembelajaran berbasis bermain.” Spiritnya bagus, tapi di lapangan, tafsirnya sering keliru. Main terus sampai capek, pembelajarannya mana?
Padahal, penelitian literasi anak usia dini justru menegaskan bahwa bermain dan membaca tidak harus dipisahkan. Di banyak negara, kegiatan membaca dini justru dikemas dalam bentuk permainan fonetik, lagu, atau aktivitas motorik halus yang menyenangkan. Jadi, bukan masalah bermainnya yang keliru, tetapi ketiadaan panduan jelas tentang pembelajaran literasi berbasis bermain.
Dalam artikel Reading Eggs, anak idealnya mulai membaca lancar di usia enam sampai tujuh tahun. Tapi kemampuan itu bukan hujan yang jatuh dari langit. Anak bukan nabi yang bisa tahu tanpa belajar. Sebaliknya, belajar membaca lahir dari paparan sejak dini, mungkin dari mendengar cerita, melihat tulisan di rumah, atau hasil dari percakapan dengan orangtua. Anak yang sejak kecil terbiasa dengan buku, akan lebih cepat mengenali pola bunyi dan bentuk huruf.
Sebaliknya, jika anak baru mengenal huruf saat berusia enam tahun, itu berarti mereka sudah kehilangan waktu dua tahun masa emas perkembangan literasi. Di usia yang seharusnya penuh rasa ingin tahu terhadap kata, mereka justru baru memulai dari nol. Dan berdasar pengalaman saya, anak-anak menjadi sulit fokus, cepat frustasi, dan merasa membaca itu sulit luar biasa. Mereka lebih suka bertanya, “Apa lauknya MBG, Pak?” Mengisi perut memang lebih mudah daripada mengisi kepala.
Bukan Sekadar Akses, Tapi Budaya
Masalah literasi kita sering dibingkai sebagai soal akses: kurangnya buku, kurangnya perpustakaan. Itu betul. Tapi ada penelitian menarik dari Anhar Dana (STIA LAN Makassar), Andika (UNHAS), dan Andi Rosman Mohamad (UNM) yang dibagikan The Conversation, di sana, ada sesuatu yang lebih pelik, budaya baca juga sangat dipengaruhi norma sosial. Membaca belum menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 503 orang responden pada tahun 2023 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagian besar responden masih beranggapan bahwa lingkungan sosialnya tidak begitu mendukung perilaku membaca buku.
Saat ditanya apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya ketika membaca buku di tempat umum? Sebagian besar responden meyakini bahwa mereka akan dicap negatif oleh masyarakat. Terdapat 30% responden (porsi terbesar) yang berpikir bahwa mereka akan dicap terlalu serius dan 23% responden (terbesar ketiga) yang berpikir bahwa mereka akan dicap sok intelek.
Temuan ini menunjukkan bahwa orang Indonesia masih menganggap perilaku membaca sebagai perilaku yang dicap negatif oleh lingkungan.
Bayangkan, anak-anak tumbuh dalam dunia di mana membaca bukan hal yang “normal”. Mereka melihat bahwa tidak membaca pun tak apa-apa, karena tidak ada yang mencontohkan sebaliknya.
Norma sosial itu membentuk cara pandang, bahwa membaca dianggap aktivitas sekolah, bukan aktivitas hidup. Maka tak heran bila bel pulang, minat membaca pun ikut padam.
Sistem yang Membiarkan Kekosongan
Kita semua patut gelisah, apatahlagi ada inkonsistensi dalam sistem pendidikan kita. Pemerintah berbicara tentang literasi nasional, tentang pentingnya membaca, tentang target Indonesia Emas 2045. Tapi di sisi lain, tidak ada kebijakan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana anak belajar membaca.
TK tidak mengajarkan membaca, SD menganggap anak sudah bisa membaca, dan orangtua tidak diberi panduan. Di tengah kekosongan itu, anak-anak menjadi korban. Mereka datang ke sekolah untuk belajar membaca, tapi kurikulum menganggap mereka sudah bisa.
Padahal, mengajar membaca permulaan bukan sekadar mengajarkan huruf. dibutuhkan pendekatan sabar, bertahap, dan penuh strategi. Guru SD kelas awal seharusnya dipersiapkan secara khusus untuk itu. Tapi kenyataannya? Banyak guru tidak mendapatkan pelatihan fonetik dasar atau metode membaca permulaan. Akibatnya, yang terjadi di kelas adalah “mengajar membaca sambil jalan”, dan namanya sambil jalan, tibanya lama sekali.
Dimulai dari Rumah
Kita tidak bisa terus menunggu kebijakan turun dari atas. Tau sendirilah. Literasi bisa dimulai dari bawah, dari kamar anak yang dibacakan buku. Anak-anak perlu melihat bahwa membaca adalah kegiatan yang menyenangkan. Orangtua adalah kunci, tidak usah menunggu Pak Mendikdasmen atau Kak Seto datang ke rumah membacakan cerita.
Penelitian Reading Eggs menegaskan bahwa anak-anak yang sering dibacakan buku sejak kecil memiliki kosa kata yang jauh lebih kaya dan motivasi membaca yang lebih tinggi. Bahkan lima belas menit membaca bersama setiap hari bisa berdampak besar terhadap perkembangan bahasa anak.
Bayangkan kalau setiap rumah di Indonesia melakukan itu. Mungkin anak-anak tidak lagi perlu bertanya, “Apa menu MBG, Pak?” hanya untuk mengalihkan diri dari belajar membaca.
Walakhir. Para guru mungkin lelah, tapi lelah ini membuat kita sadar, kalau tidak ada yang memulai, tidak akan ada yang perbaikan. Perubahan itu, seperti halnya membaca, selalu dimulai dengan satu langkah kecil, satu huruf yang menjadi kata, satu kata yang menjadi kalimat, satu kalimat akan membawa perubahan. Mudah-mudahan.
Sumber gambar: Shutterstock

Guru PJOK dan pegiat literasi di Bantaeng. Penulis buku kumpulan esai, Jika Kucing Bisa Bicara (2021) dan anggota redaksi di Paraminda.com.

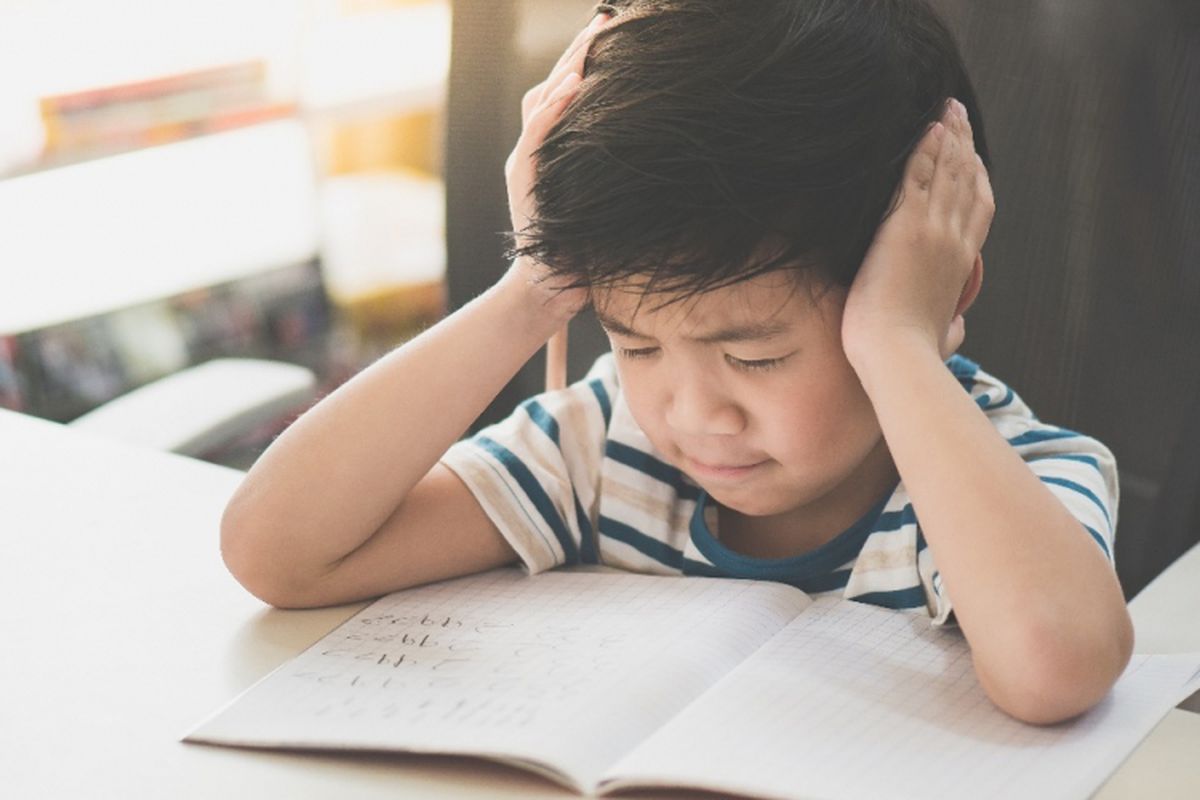
Leave a Reply