Mul adalah pemuda yang lahir dan tumbuh besar di Ibu Kota Kabupaten Bantaeng. Sehari-hari ia akrab dengan jalan beraspal, deretan pertokoan dan kerumunan orang di pasar. Khas orang kota kecil, Bantaeng.
Orangtua Mul berasal dari Kayu Loe, sebuah desa yang berjarak sekitar 20 kilometer dari pusat kota. Mereka mulai menetap di kota pada akhir tahun 1980-an untuk mencari kehidupan yang lebih baik, seperti banyak orang desa lainnya kala itu.
Sebagai anak yang dibesarkan di ibu kota kabupaten, bertani jelas bukan pilihan utama dalam menjalani keseharian. Mul menghabiskan waktunya dengan aktif berorganisasi. Melalui organisasi, ia membangun jejaring yang kelak membawanya bekerja di Payopayo dan Oase, dua lembaga yang fokus pada isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Namun, hidup punya caranya sendiri untuk membelokkan arah seseorang. Pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020-2021 membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, pendapatan, bahkan arah hidup. Kota-kota menjadi pusat keterbatasan, dan banyak orang akhirnya memilih pulang ke kampung halaman. Begitu pun Mul. Dalam situasi yang tidak menentu itu, ia memutuskan untuk menetap di Kayu Loe, kampung orang tuanya, yang sebelumnya hanya sesekali ia kunjungi.
Di Kayu Loe, Mul menghadapi kehidupan berbeda. Tak ada ritme kehidupan kota yang riuh. Ia mulai fokus pada kebun keluarga yang tidak dirus dengan baik, setidaknya dari sudut pandang seorang yang terbiasa berorganisasi. Perlahan, Mul mulai menyelami aktivitas yang bersentuhan langsung dengan lahan, aktivitas yang dulu menjadi tumpuan hidup orangtuanya.
Ia menanam jagung, kopi, ubi, dan berbagai tanaman lainnya. Bukan semata untuk bertahan hidup, tetapi sebagai upaya untuk memahami akar dirinya dan mungkin saja menatap masa depan yang lebih mandiri. Mungkin ya!
Sebagai orang yang terbiasa berorganisasi dan bekerja dengan sistem, Mul berniat menjalani aktivitas bertani dengan pendekatan yang terencana dan terukur. Ia mencatat dengan teliti setiap proses dan biaya produksi jagung yang ia tanam selama lima bulan. Dari tahap pembukaan lahan, penanaman, pemupukan, hingga panen. Catatan sederhana itu, mungkin tampak remeh, tetapi sesungguhnya menjadi satu praktik penting dalam kehidupan bertani.
Dengan mencatat seluruh proses dan biaya, Mul bisa menghitung secara akurat berapa besar modal yang dikeluarkan, berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, hingga berapa keuntungan atau kerugian yang ia peroleh. Dari sana, ia bisa membuat keputusan yang lebih tepat untuk musim tanam berikutnya. Apakah ia perlu mengganti varietas jagung? Apakah pola tanamnya efektif? Apakah perlu memperbaiki manajemen air? Semua itu hanya bisa dijawab dengan data yang ia kumpulkan sendiri.
Pencatatan menjadi ruang refleksi yang penting. Petani yang tekun mencatat akan lebih peka terhadap perubahan-perubahan kecil di ladangnya. Mereka tidak hanya bekerja berdasarkan kebiasaan turun-temurun atau “katanya orang tua dulu begini”, tapi benar-benar memahami kondisi lahannya, pasarnya, dan dirinya ssendiri
Di tengah industrialisasi pertanian, yang digerakkan oleh korporasi besar dengan alat produksi canggih dan jaringan distribusi yang luas, petani dengan lahan kecil dengan mudah digilas. Catatan Mul, yang saya peroleh dari Bung Ahmad Pasallo, bisa menjadi adalah modal awal untuk memulai memahami lebih jauh situasi yang dihadapi petani, khususnya di Bantaeng.
Dari Tanam ke Hitung-hitungan
Mul menggarap lahan seluas 50 are (0,5 hektar). Prosesnya berlangsung dari awal April hingga pertengahan September 2020, selama kurang lebih 166 hari. Dalam catatannya, ia merinci semua pengeluaran; benih, herbisida, insektisida, pupuk, upah kerja, hingga biaya pasca panen. Total biaya produksi yang ia keluarkan adalah Rp3.785.000.

Dengan luas lahan garapan sebesar 50 are, Mul menanam 8 kilogram benih jagung. Selama 166 hari, atau kurang lebih lima bulan setengah, ia menjalani seluruh proses bertani; dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Hasil yang ia peroleh adalah 2.568 kilogram jagung pipilan kering. Dengan harga pasar saat itu sebesar Rp 3.000 per kilogram, total pendapatan yang ia peroleh mencapai Rp7.704.000.
Namun, angka tersebut bukanlah keuntungan bersih. Setelah dikurangi seluruh biaya produksi, laba kotor yang Mul peroleh hanyalah sekitar Rp3.919.000. Jika dibagi rata ke dalam masa kerja 166 hari, pendapatan per harinya berkisar Rp23.613. Artinya, bila dihitung secara bulanan, penghasilannya setara dengan Rp708.420, jauh di bawah standar upah minimum di Sulawesi Selatan, dan nyaris tak cukup buat menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi untuk menabung atau berinvestasi.
Angka-angka ini jelas membuat siapa pun jadi pesimis terhadap masa depan petani kecil. Namun, dari catatan rinci yang Mul buat selama proses produksi, kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga: pemahaman.
Pencatatan yang dilakukan Mul membuat seluruh proses bertani menjadi terbuka dan terukur. Pemahaman kita menjadi terbuka di titik mana biaya membengkak, di fase mana tenaga kerja paling intensif dibutuhkan, dan berapa besar hasil yang sebenarnya bisa diharapkan. Semua itu menjadi bekal penting untuk memperbaiki strategi dalam bertani jagung.
Lebih jauh lagi, pencatatan ini bisa menjadi dasar bagi pengembangan pengetahuan kolektif di kalangan petani. Jika setiap petani melakukan hal serupa, maka dari banyak catatan individual bisa disusun gambaran besar yang merefleksikan situasi riil pertanian di tingkat tapak.
Informasi ini bisa menjadi alat untuk menyusun strategi bersama, dari pola tanam, pengadaan pupuk, sistem pemasaran kolektif, hingga perencanaan diversifikasi usaha.
Yang lebih penting, catatan-catatan ini bisa menjadi dasar untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih adil. Pemerintah, misalnya, dapat menyusun program bantuan atau penetapan harga dasar komoditas dengan merujuk pada data yang bersumber langsung dari pengalaman petani. Ini akan menciptakan kebijakan yang lebih kontekstual, tidak hanya berdasarkan asumsi makro atau kepentingan korporasi besar.
Pengalaman Mul menjadi bukti nyata bahwa menjadi petani di masa kini, tidak cukup hanya dengan kekuatan fisik atau keterampilan teknis. Diperlukan wawasan, ketekunan belajar, dan kemampuan analitis untuk bisa bertahan dan berkembang. Makin beratlah sudah menjadi petani.
Dan jika menjadi petani menjadi semakin berat, itu artinya petani butuh saling berbagi, biar bebannya tidak dipikul sendiri-sendiri. Dengan demikian petani butuh wadah untuk saling berbagi. Wadah itu adalah organisasi, petani butuh berorganisasi.
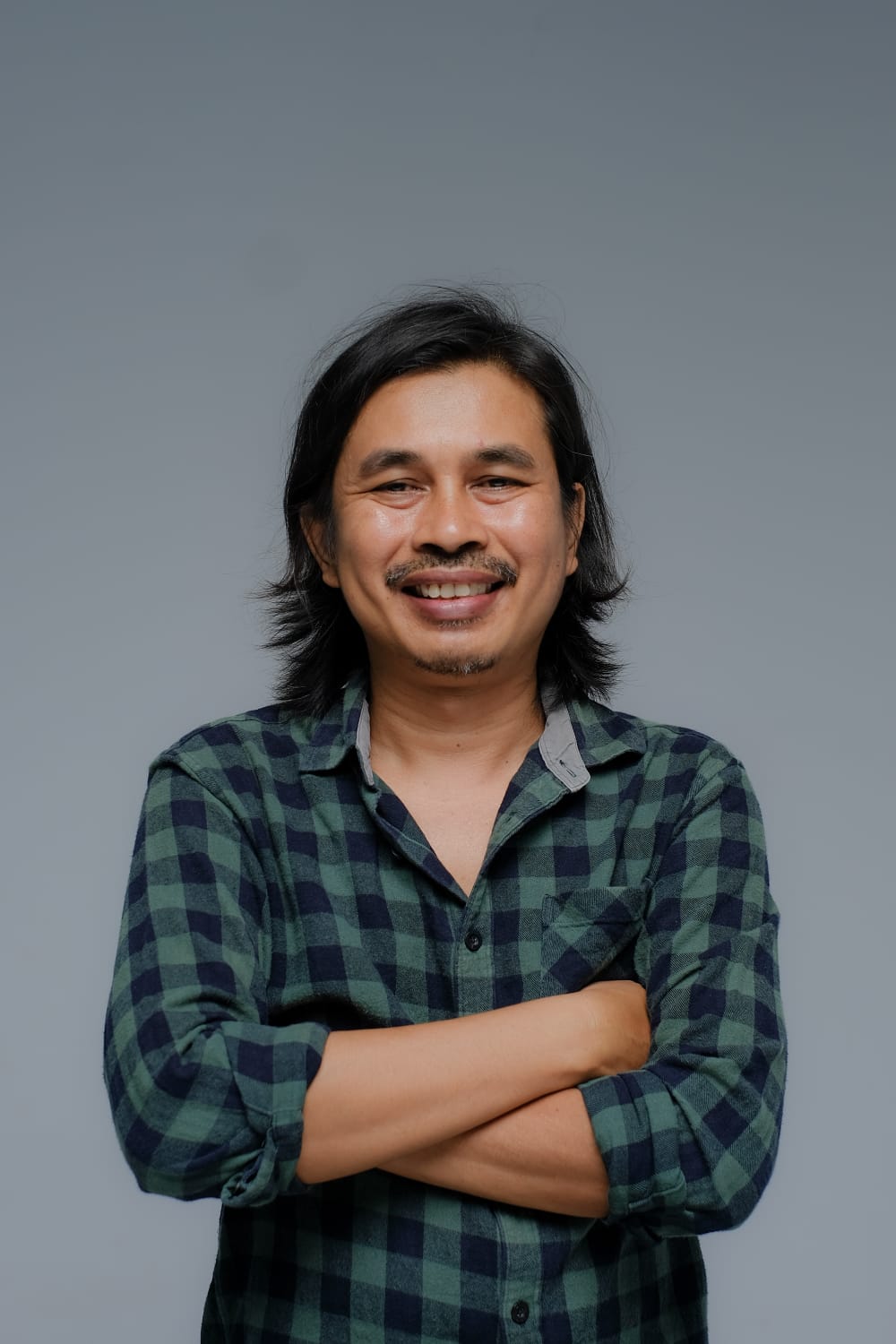
Penggiat lingkungan asal Bantaeng, tinggal di Jakarta. Buku favorit Kepulauan Nusantara. Film favorit “Naga Bonar”


Leave a Reply