Budaya adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dimiliki oleh sekelompok orang. Budaya merupakan aspek penting yang membentuk identitas dan cara hidup suatu masyarakat. Dalam masyarakat yang majemuk, budaya memainkan peran yang sangat penting dalam mempersatukan masyarakat. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki keragaman budaya dan tradisi tersendiri yang membuatnya unik dan menarik.
Zaman memang telah berkembang dan berubah. Namun, sebagian masyarakat masih berpegang teguh pada budaya yang telah diwariskan turun temurun. Budaya tidak membatasi kelas ekonomi, budaya menyentuh segala lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat kelas bawah hingga kelas atas. Misalnya, budaya gotong royong sebagai identitas yang sudah melekat pada jati diri masyarakat. Gotong royong memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat, nilai budaya ini mengajarkan untuk saling membantu dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.
Kabupaten Bantaeng yang dijuluki sebagai Butta Toa atau tanah tua, sebagian besar masyarakatnya adalah petani, waktu pagi dan sore banyak dihabiskan di sawah dan di ladang. Tidak mengherankan jika aktivitas bertani telah membentuk budayanya sendiri sehingga semakin mengokohkan identitas masyarakat itu sendiri.
Di Batulabbu, sebuah kampung yang berjarak kurang lebih 19 kilometer dari pusat kota Bantaeng, terdapat sebuah budaya gotong royong, masyarakat biasa menyebut dengan istilah a’baribbasa dan a’karueng. A’baribbasa jika diartikan secara tekstual berarti aktivitas pagi, awalan a’ menunjukkan aktivitas sementara baribbasa berarti waktu pagi. Sama halnya dengan istilah a’karueng awalan a’ menunjukkan aktivitas dan karueng berarti waktu sore.
Sesuai dengan ejaannya, a’baribbasa sebenarnya adalah aktivitas bertani yang dilakukan di pagi hari. Aktivitasnya bermacam-macam, mulai dari menanam padi, memanen, membajak, dan pekerjaan pertanian lainnya. Namun, tidak semua aktivitas bertani disebut a’baribbasa. Istilah ini digunakan masyarakat apabila akan melakukan aktivitas bertani dalam ukuran besar yang membutuhkan banyak orang.
Sehari sebelum a’baribbasa atau a’karueng, pemilik lahan akan mendatangi kerabat, tetangga, dan sanak saudara lainnya guna mengabari tentang aktivitas besar yang akan dilakukan di sawah atau di ladang. Namun, karena besarnya rasa kebersamaan, terkadang beberapa orang datang membantu tanpa diberi informasi, mereka hanya mendengar kabar dari mulut ke mulut.
Sementara itu, a’karueng sebenarnya hampir sama dengan a’baribbasa, sama-sama aktivitas bertani dalam ukuran yang besar dan membutuhkan banyak orang, yang membedakan hanya soal waktu, di mana aktivitas bertaninya dimulai pada sore hari. Dalam budaya a’karueng pemilik lahan hanya menyediakan makanan ringan berupa kue dan minuman sebagai pelengkap.
Budaya a’baribbasa dan a’karueng bukan sekadar aktivitas bertani biasa di sawah atau di ladang. Budaya ini memiliki makna yang dalam pada aktivitas bertani masyarakat. Nilai dalam budaya ini mencerminkan sikap gotong royong yang menumbuhkan rasa kerja sama, solidaritas, dan kepentingan bersama. Bekerja sama dalam mencapai tujuan, meningkatkan rasa kebersamaan dalam bingkai solidaritas, dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu.
Jika membandingkan pekerja profesional pada umumnya yang menerima imbalan uang setelah melakukan pekerjaan, dalam budaya a’baribbasa dan a’karueng masyarakat tidak menerima imbalan sama sekali, pemilik lahan hanya cukup menyediakan makanan berat sebagai tanda terima kasih kepada orang-orang yang telah ikut membantu.
Keadaan zaman yang maju pesat, telah mengubah cara pandang masyarakat dalam melihat banyak hal. Hampir semua sendi-sendi dalam hidup bermasyarakat telah diukur dari nominal uang. Budaya a’baribbassa dan a’karueng ibarat payung peneduh di tengah-tengah hujan materialistik selama ini pun mulai memudar. Pudarnya budaya a’baribbassa dan a’karueng ini dipengaruhi oleh penemuan teknologi, dan pilihan jenis tanaman yang dipilih untuk dibudidayakan dalam mengolah sawah dan kebun.
Teknologi yang berkembang seperti hand traktor dalam membajak, telah mengganti sapi maupun kuda dalam membajak sawah dan ladang. Pilihan jenis tanaman yang dulunya berupa jagung ataupun kacang tanah, telah berganti menjadi tanaman tahunan untuk memenuhi kepentingan pasar seperti cengkih, kakao, dan tanaman buah-buahan seperti durian.
Kedepan, budaya ini tentu akan menghadapi tantangan yang lebih besar lagi jika melihat pola bertani masyarakat yang berangsur mengalami perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh arus teknologi yang semakin hari semakin berkembang, membuat masyarakat mulai meninggalkan pola bertani konvensional. Dalam penggunaan alat-alat pertanian misalnya, alat pertanian modern dapat melakukan pekerjaan yang lebih cepat dan efisien, sehingga akan mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia.
Secara tidak sadar masyarakat akan dihadapkan pada situasi yang dilematis, menggunakan alat-alat pertanian yang modern dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Namun, di sisi lain akan melemahkan ikatan sosial karena kurangnya lagi ketergantungan tenaga manusia yang pada puncaknya akan menggerus rasa gotong royong yang selama ini terbingkai dalam budaya a’baribbasa dan a’karueng.
Catatan: Tulisan ini sudah dimuat dalam buku, Bantaeng Satu Negeri Seribu Cerita (2025), hal. 132-134.
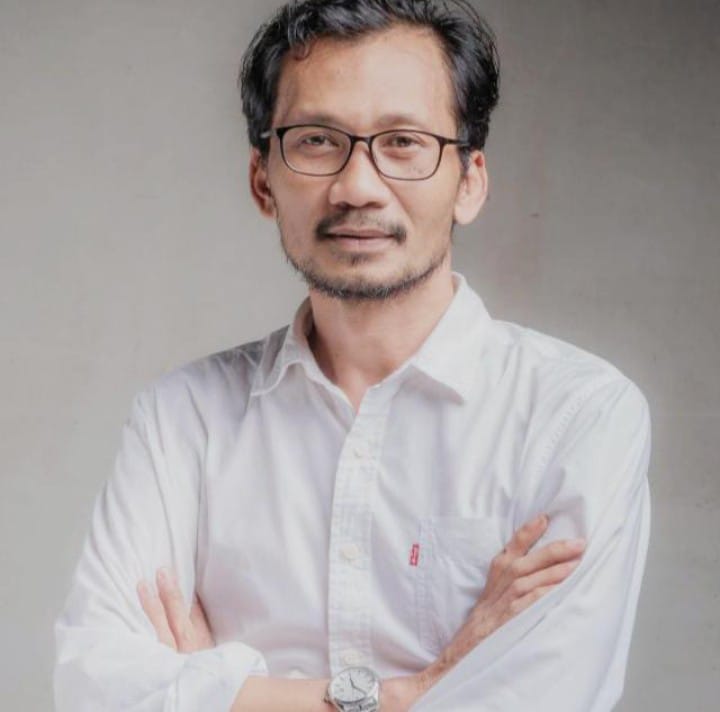
sejak 2010 bekerja dalam pelestarian lingkungan dengan membangun organisasi Balang Institue. Perkumpulan OASE adalah lembaga kedua yang dibangunnya dan saat ini menjabat sebagai Ketua. Dari dua Lembaga ini, ia menempa pengetahuan dan pengalamannya belajar terkait kehutanan, pertanian berkelanjutan, good governance, dan perubahan iklim serta mediasi konflik lahan dan sumber daya alam. Ia memiliki mimpi akan ruang hidup yang adil dan berkelanjutan.


Leave a Reply