Membongkar arogansi ilmiah bukanlah pekerjaan sesaat, melainkan proses panjang yang melibatkan transformasi individu, pembaruan institusi, dan perubahan paradigma budaya pengetahuan.
Arogansi ilmiah telah tumbuh bukan hanya dari kepribadian para pelaku ilmu, tetapi juga dari sistem pendidikan, politik pendanaan penelitian, hingga cara masyarakat memandang sains. Oleh karena itu, strategi mengatasinya harus bersifat menyeluruh dan berlapis.
Langkah pertama, reintegrasi filsafat dalam pendidikan sains. Pendidikan ilmiah modern sering kali terfokus pada keterampilan teknis dan pencapaian praktis, sementara dimensi reflektifnya terpinggirkan. Kurikulum yang menggabungkan filsafat ilmu, sejarah sains, dan etika penelitian sejak tahap awal pendidikan dapat menumbuhkan kesadaran epistemik yang mencegah munculnya klaim absolutis. Mahasiswa biologi, misalnya, tidak hanya mempelajari genetika dari sisi mekanistik, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan ekologis dari rekayasa genetik.
Langkah kedua, membangun budaya dialog lintas disiplin. Arogansi ilmiah sering muncul ketika satu disiplin merasa memiliki monopoli kebenaran. Dengan menciptakan forum di mana ilmuwan, filsuf, seniman, dan praktisi sosial dapat berdiskusi setara, kita membuka ruang bagi perspektif yang saling memperkaya. Dalam dialog ini, filsafat berfungsi sebagai jembatan yang memfasilitasi terjemahan konsep antar-disiplin, sehingga perbedaan metode dan bahasa tidak menjadi penghalang komunikasi.
Langkah ketiga, reformasi sistem penghargaan akademik. Saat ini, banyak institusi penelitian memberikan penghargaan terutama berdasarkan jumlah publikasi atau besaran hibah riset yang diperoleh. Sistem ini mendorong kompetisi sempit dan memelihara ego akademik. Sebagai gantinya, perlu dikembangkan mekanisme penghargaan yang juga menilai kontribusi terhadap kolaborasi lintas disiplin, keterbukaan data penelitian, serta upaya membangun literasi publik. Dengan demikian, keberhasilan ilmiah tidak lagi semata-mata diukur dari akumulasi prestasi pribadi, tetapi dari dampak kolektif terhadap pengetahuan dan masyarakat.
Langkah keempat, menanamkan prinsip transparansi dan keterbukaan. Keterbukaan metodologi, data, dan keterbatasan hasil penelitian adalah cara efektif untuk mencegah arogansi ilmiah. Semakin publik memahami proses dan batas-batas sains, semakin kecil kemungkinan ilmuwan dipandang (atau memandang dirinya sendiri) sebagai otoritas yang tak tergugat. Prinsip ini juga membangun kepercayaan publik sekaligus meminimalkan risiko manipulasi hasil penelitian untuk kepentingan tertentu.
Langkah kelima, memperkuat pendidikan etika penelitian. Etika bukan sekadar prosedur formal untuk memenuhi syarat publikasi, melainkan panduan moral yang membentuk integritas ilmuwan. Pelatihan etika yang serius harus mengajak ilmuwan memikirkan dilema konkret, seperti penggunaan teknologi pengawasan, eksploitasi sumber daya alam, atau eksperimen yang melibatkan subjek rentan. Etika di sini bukan “penghalang” kemajuan, melainkan pagar yang memastikan kemajuan tidak berubah menjadi bumerang.
Langkah terakhir, menghidupkan kembali nilai pengakuan ketidaktahuan. Dalam budaya akademik, sering kali ada tekanan untuk selalu memiliki jawaban. Padahal, mengakui ketidaktahuan adalah tanda kedewasaan intelektual dan pintu masuk bagi inovasi. Forum-forum akademik perlu memberi ruang bagi ilmuwan untuk mengajukan pertanyaan terbuka tanpa rasa takut dianggap lemah. Dengan demikian, ilmu kembali menjadi petualangan kolektif menuju kebenaran, bukan ajang pembuktian supremasi intelektual.
Strategi-strategi ini saling terkait dan hanya efektif bila dijalankan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pengetahuan. Arogansi ilmiah tumbuh dalam ruang yang tertutup, hierarkis, dan penuh tekanan kompetitif; ia akan surut ketika ruang itu dibuka, hubungan menjadi egaliter, dan motivasi diarahkan pada pencarian kebenaran bersama. Dalam arti ini, membongkar arogansi ilmiah bukan hanya tugas ilmuwan atau filsuf, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat yang menggantungkan masa depannya pada kebijaksanaan pengetahuan.
Kredit gambar: Kompas.com

Lahir di Sorowako, 1 Februari 1969. Menempuh studi pada Jurusan Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Sewaktu mahasiswa, ia pernah menjabat Ketua Umum HMI-MPO Cabang Makassar, 1996-1997. Saat ini ia berkecimpung dalam dunia usaha, sebagai Direktur Utama PT. Pontada Indonesia. Telah mengarang buku puisi berjudul, Ziarah Cinta (2015).

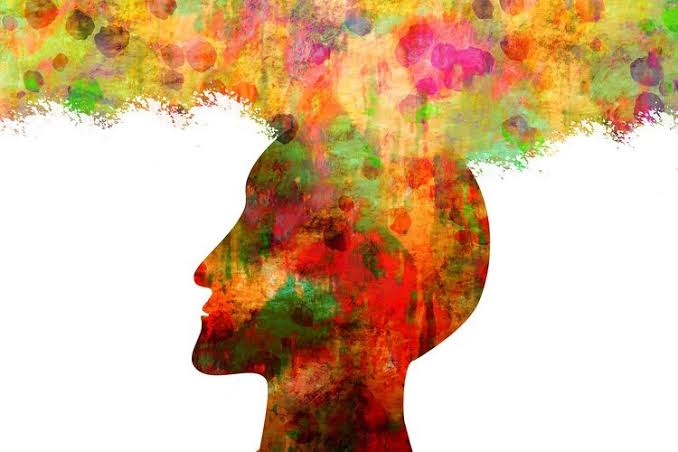
Leave a Reply