Di tengah derasnya arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita menyaksikan paradoks yang semakin nyata: semakin tinggi pencapaian intelektual, semakin besar pula potensi munculnya arogansi ilmiah.
Fenomena tersebut tidak hanya berwujud pada kesombongan personal seorang ilmuwan atau akademisi, tetapi juga pada cara suatu komunitas ilmiah memandang kebenaran—seolah-olah pengetahuan yang mereka miliki adalah puncak yang tak dapat digugat. Klaim ini sering kali mengabaikan kenyataan mendasar bahwa setiap ilmu memiliki keterbatasan epistemik, bias metodologis, dan horizon historis yang membentuknya.
Ironisnya, arogansi ini sering lahir dari minimnya pemahaman filsafat—khususnya filsafat ilmu—yang mestinya menjadi benteng kerendahan hati intelektual. Filsafat, dengan wataknya yang mempertanyakan asumsi paling mendasar, melatih manusia untuk menyadari keterbatasan perspektifnya.
Namun, di era yang terobsesi pada kecepatan inovasi, filsafat kerap dipinggirkan, dianggap tidak praktis, atau bahkan usang. Akibatnya, banyak praktisi sains dan teknologi terjebak dalam keyakinan sempit bahwa metodologi mereka adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran.
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan paradigma pendidikan modern. Pendidikan tinggi cenderung menekankan spesialisasi sempit dan penguasaan teknis, namun mengabaikan pembekalan filosofis yang membentuk kesadaran epistemik.
Mahasiswa sains jarang diperkenalkan pada filsafat pengetahuan; mahasiswa teknik jarang berdialog dengan filsafat etika; bahkan mahasiswa sosial sering terjebak dalam relativisme tanpa memahami landasan ontologis dan epistemologis dari klaim yang mereka buat. Akibatnya, terjadi jurang antara kecakapan teknis dan kebijaksanaan intelektual.
Sejarah memberikan banyak pelajaran tentang bahaya arogansi ilmiah. Tidak sedikit teori yang dulu diagungkan sebagai “final” kemudian runtuh oleh temuan baru. Dari keyakinan geosentris abad pertengahan, hingga teori Newton yang dikoreksi oleh relativitas Einstein, kita melihat pola yang berulang: kebenaran ilmiah selalu bersifat sementara dan terbuka untuk revisi. Filsafat membantu kita memahami bahwa perubahan ini adalah bagian alami dari perkembangan pengetahuan, bukan tanda kelemahan ilmu. Tanpa kesadaran ini, ilmuwan mudah terjebak dalam ilusi absolutisme.
Tulisan ini berangkat dari kegelisahan bahwa arogansi ilmiah bukan sekadar masalah etika personal, melainkan problem epistemologis yang mengancam kualitas peradaban. Dengan bahasa akademik yang tetap dapat diakses pembaca umum, esai ini akan membahas hakikat arogansi ilmiah, peran vital filsafat sebagai penuntun kerendahan hati intelektual, dampak negatif minimnya pemahaman filsafat, serta strategi membangun budaya ilmiah yang rendah hati namun tetap kritis.
Hakikat dan Manifestasi Arogansi Ilmiah
Arogansi ilmiah bukanlah sekadar kesombongan personal yang lahir dari keberhasilan akademis atau penemuan besar. Ia adalah sikap epistemik—cara berpikir dan memandang dunia—yang menempatkan pengetahuan yang dimiliki seseorang atau kelompok sebagai standar tunggal kebenaran.
Dalam bentuk paling ekstrem, arogansi ilmiah menafikan kemungkinan bahwa kebenaran bisa datang dari luar paradigma yang dianut, baik dari disiplin ilmu lain, kebijaksanaan tradisional, maupun dari refleksi filosofis dan spiritual.
Secara konseptual, arogansi ilmiah dapat dipahami sebagai gabungan antara overconfidence bias dan epistemic closure. Overconfidence bias membuat seseorang menilai kemampuan dan pengetahuannya lebih tinggi dari kenyataan. Epistemic closure terjadi ketika individu atau komunitas ilmiah menutup diri dari informasi atau argumen yang tidak sesuai dengan kerangka berpikir mereka. Kedua hal ini sering muncul secara bersamaan, menciptakan ruang intelektual yang steril dari kritik.
Sejarah sains memberi banyak contoh fenomena ini. Dalam era pra-Kopernikus, mayoritas ilmuwan Eropa meyakini teori geosentris bukan hanya sebagai penjelasan terbaik, tetapi sebagai satu-satunya penjelasan yang benar.
Penolakan terhadap gagasan heliosentris bukan semata-mata karena kurangnya bukti, tetapi juga karena keyakinan bahwa kerangka Aristotelian-Ptolemaik adalah final.
Demikian pula, teori Newton yang pada abad ke-18 dianggap sebagai hukum mekanika absolut ternyata mengalami revisi fundamental oleh teori relativitas Einstein pada awal abad ke-20.
Namun, arogansi ilmiah tidak hanya terjadi di masa lalu. Dalam era digital, kita melihatnya dalam bentuk “teknokratisme”—keyakinan bahwa semua masalah sosial dapat dipecahkan dengan algoritma dan data, tanpa mempertimbangkan kompleksitas etis, budaya, dan psikologis manusia.
Para pendukung ekstrem teknologi kecerdasan buatan, misalnya, terkadang berbicara seolah-olah model matematis yang mereka bangun mampu memahami realitas manusia secara total. Mereka lupa bahwa data hanyalah representasi, bukan realitas itu sendiri.
Manifestasi lain dari arogansi ilmiah adalah scientific reductionism—pandangan bahwa semua fenomena dapat dijelaskan sepenuhnya oleh satu tingkat realitas, biasanya yang bersifat fisik atau material.
Pandangan tersebut cenderung mengabaikan dimensi nonmaterial seperti kesadaran, makna, atau nilai, yang meskipun sulit diukur, memiliki peran vital dalam kehidupan manusia. Reduksionisme semacam ini sering mempersempit ruang dialog antara sains dan filsafat, bahkan antara sains dan agama.
Jika tidak dikendalikan, arogansi ilmiah dapat mengikis etos dasar ilmu pengetahuan itu sendiri: keterbukaan terhadap kritik, kesadaran akan keterbatasan, dan kerendahan hati di hadapan kompleksitas realitas. Di sinilah filsafat menjadi penting—bukan sebagai pelengkap mewah, tetapi sebagai fondasi yang menjaga ilmu tetap manusiawi dan terbuka.
Kredit gambar: Rumah Filsafat

Lahir di Sorowako, 1 Februari 1969. Menempuh studi pada Jurusan Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Sewaktu mahasiswa, ia pernah menjabat Ketua Umum HMI-MPO Cabang Makassar, 1996-1997. Saat ini ia berkecimpung dalam dunia usaha, sebagai Direktur Utama PT. Pontada Indonesia. Telah mengarang buku puisi berjudul, Ziarah Cinta (2015).

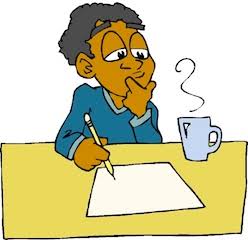
Leave a Reply