Pendidikan seharusnya menjadi ruang pembebasan, tempat berlangsungnya transformasi intelektual dan karakter peserta didik.
Namun, dalam praktiknya, dunia pendidikan di Indonesia semakin menunjukkan wajah yang sarat dengan seremonial, angka, dan formalitas semu. Di balik gemerlap kegiatan pelatihan, seminar, dan diklat, kompetensi guru yang dilaksanakan silih berganti, tersimpan kegelisahan yang mendalam: benarkah semua itu berdampak nyata pada kualitas pembelajaran?
Kegiatan-kegiatan pendidikan hari ini kerap dibungkus dalam kemasan acara yang megah, tetapi miskin makna. Kalender pendidikan diwarnai oleh serangkaian pelatihan, bimbingan teknis, workshop, dan kegiatan seremonial lainnya.
Guru-guru tidak hanya menjadi peserta pelatihan, tapi juga sibuk menjadi panitia, pengurus, bahkan event organizer kegiatan pelatihan itu sendiri. Kesibukan ini menciptakan distorsi terhadap peran utama seorang pendidik—mendidik.
Kritik yang mengemuka bukan tanpa alasan. Diklat-diklat pengembangan kompetensi guru yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kualitas, justru sering kali terjebak pada logika kuantitas.
Ukuran keberhasilannya dilihat dari seberapa banyak guru yang dilatih, seberapa banyak sertifikat yang dibagikan, bukan pada sejauh mana pelatihan itu mengubah cara guru mengajar, berinteraksi dengan siswa, dan meningkatkan hasil belajar.
Hasil pelatihan seringkali tidak ditindaklanjuti dengan pendampingan berkelanjutan, monitoring implementasi, atau refleksi kritis terhadap praktik pengajaran.
Padahal, outcome—bukan sekadar output—harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan pelatihan. Outcome yang dimaksud adalah peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, tumbuhnya motivasi intrinsik guru dalam mengembangkan diri, dan meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap tugas profesi.
Sayangnya, yang sering terjadi justru sebaliknya: guru menjadi lelah, terpecah fokusnya, dan menjadikan pelatihan sebagai rutinitas administratif yang harus dijalani, bukan kebutuhan yang tumbuh dari kesadaran profesional.
Di sinilah letak ironi pendidikan kita: sebuah sistem yang tampak sibuk berbenah, tetapi berjalan di tempat. Seremonial menjadi citra, bukan substansi. Akreditasi, sertifikasi, dan pelaporan administratif mengambil porsi lebih besar daripada pertanyaan reflektif: apakah siswa kita belajar lebih baik hari ini dibanding kemarin?
Pendidikan memerlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan transformatif. Pelatihan guru harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil di kelas, disertai dengan proses reflektif dan evaluasi yang berkelanjutan. Lebih dari itu, perlu ada keberanian untuk memutus mata rantai budaya administratif yang menyesatkan, dan menggantinya dengan budaya belajar yang otentik, kritis, dan bermakna.
Tanpa itu semua, pendidikan kita hanya akan menjadi panggung besar dengan banyak aktor, naskah yang panjang, tetapi kehilangan makna—karena tidak pernah benar-benar menyentuh inti dari proses belajar itu sendiri.
Harapan akan perubahan pendidikan yang lebih bermakna, sempat menguat ketika pemerintah memutuskan memisahkan urusan pendidikan dasar dan menengah dari pendidikan tinggi. Langkah ini diharapkan memberi ruang bagi kementerian untuk lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini menjadi beban panjang dunia pendidikan, khususnya di jenjang dasar dan menengah—dari kualitas guru, kurikulum yang relevan, hingga ekosistem belajar yang manusiawi.
Di bawah kepemimpinan Prof. Abdul Mu’ti, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, publik mulai mendengar lebih banyak narasi tentang pentingnya pendidikan yang berdampak dan bermutu untuk semua. Narasi ini bukan sekadar jargon, tetapi lahir dari kepedulian terhadap kesenjangan mutu pendidikan yang masih nyata di berbagai penjuru negeri. Retorika tentang pendidikan yang mencerahkan, inklusif, dan membebaskan menjadi lebih sering digaungkan.
Namun, pertanyaannya tetap menggantung: apakah narasi ini akan sungguh menjadi solusi konkrit? Apakah akan lahir perubahan yang sistemik dan menyentuh hingga ruang kelas yang paling terpencil? Atau justru akan kembali menjadi barisan kata-kata yang indah, tetapi tak berjejak?
Wallahu a’lam—kita hanya bisa berharap dan terus mengawal agar semangat perubahan itu tidak terhenti di podium-podium pidato, tetapi benar-benar hidup dalam praktik pendidikan sehari-hari. Karena hanya dengan itulah pendidikan Indonesia bisa bangkit, bukan hanya sibuk berbenah di permukaan, tetapi juga bergerak menuju esensinya yang sejati: membebaskan dan memanusiakan.
Kredit gambar: Blok Bojonegoro

- Lahir di Bantaeng, 12 Desember 1983. Ia merupakan seorang tenaga pendidik di SMKN 2 Bantaeng, sekaligus penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2023 untuk Program Doktoral Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Di luar profesinya sebagai pendidik, Firdaus aktif membagikan pemikiran dan kreativitasnya melalui berbagai platform digital. Ia merupakan kreator konten di kanal YouTube Firdaus Manaf, aktif di TikTok dengan nama pengguna @firdaus.manaf, serta menulis di blog pribadinya www.makassaredukasi.online, yang berfokus pada isu-isu pendidikan dan perkembangan literasi digital di daerah. Kini, menjabat selaku Sekretaris KONI Bantaeng.

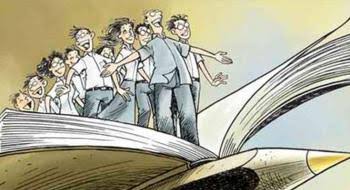
Leave a Reply